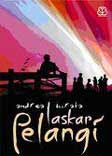Alhamdulillah, dimuat di Koran Tempo, Rabu, 12 Maret 2008
Harga Minyak dan Kebijakan Sektor Hulu Migas
Edy Hafidl*
Harga minyak mentah dunia kembali mencatat rekor baru, yakni mencapai US$103,05 per barel pada perdagangan komoditas akhir pekan, sebuah pencapaian harga yang tak pernah terjadi dalam sejarah perdagangan minyak dunia. Dampak negatif lonjakan harga minyak—yang telah terjadi sejak paruh kedua 2007—telah banyak diulas, telah nampak di depan mata, bahkan telah dialami oleh sebagian besar anak negeri. Dahulu, jika harga minyak dunia naik, maka negara akan mendapatkan `rezeki nomplok`, yakni apa yang dinamakan dengan windfall profit. Namun, kini, alih-alih mendapatkan rezeki nomplok, lifting (asumsi tingkat produksi) minyak di APBN 2008 justru diturunkan, sementara ironisnya, pajak barang impor untuk kegiatan minyak dan gas bumi (migas) justru diturunkan hingga nol persen.
Apa yang salah dalam kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi di negeri ini? Harga minyak dunia naik, mengapa windfall profit tak bisa diraih oleh negara kita? Disadari atau tidak, secara ekonomi-politik, sebenarnya kebijakan tentang pengelolaan minyak dan gas bumi suatu negara, adalah cermin dari karakter kepemimpinan sebuah negara. Sejarah membuktikan bahwa karakter kepemimpinan kepala negara, akan memiliki implikasi langsung ataupun tidak langsung, terhadap implementasi kebijakan di sektor minyak dan gas bumi. Tengoklah kepemimpinan Fidel Castro yang non-kompromis—untuk tidak dikatakan otoriter— yang dengan tanpa kompromi menasionalisasi perusahaan-perusahaan migas asing. Namun, selayaknya, terlepas apapun karakter kepemimpinan negara, kebijakan tak lain haruslah ditujukan bagi kepentingan negara: untuk pencapaian kemakmuran rakyatnya.
Entahlah mazhab ekonomi energi mana yang dianut negeri ini. Sejumlah hal yang terjadi di negeri ini berkaitan dengan kebijakan di sektor minyak dan gas bumi sejak paruh kedua 2007 hingga hari ini, sangatlah menggelikan, plin-plan, tidak jelas. Biarlah masyarakat yang akan menilai, apakah ada kaitan antara kebijakan di sektor energi minyak dan gas bumi ini, dengan karakter pemimpin negeri ini.
Simaklah secara kronologis, apa yang terjadi sejak 16 Agustus 2007. Ketika itu, pada Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2008, presiden mengumumkan asumsi harga minyak di APBN 2008 sebesar US$60 per barel, dengan lifting minyak dalam RAPBN 2008 sebanyak 1,034 juta barel per hari (bph). Untuk diketahui khalayak bahwa urgensi peghitungan asumsi harga minyak dunia dan lifting minyak di APBN adalah untuk mengetahui seberapa besar pendapatan negara dari sektor minyak dan gas bumi. Jadi, rumus untuk asumsi pendapatan negara dari migas di APBN adalah: asumsi harga minyak dunia, dikalikan asumsi lifting minyak, dikalikan hari produksi di tahun takwim, maka didapatkankanlah pendapatan negara dari sektor migas.
Namun, melihat kecenderungan harga minyak dunia yang merangkak naik, ditambah lagi dengan pesimisme tentang kemampuan pemerintah/Pertamina dan kontraktor production sharing (KPS) migas atau kontraktor bagi hasil (KBH) dalam pencapaian peningkatan produksi, maka, tepat satu bulan setelah itu, yakni 17 September, setelah melakukan rapat kerja dengan DPR, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral merevisi lifting minyak 2008, menjadi hanya maksimal 1 juta bph.
Khalayak terpaksa harus menerima penjelasan tentang alasan `penyesuaian` lifting itu dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yakni pertama, produksi minyak terbesar baru bisa dicapai pada semester kedua 2008. Beberapa lapangan minyak yang akan memproduksi minyak skala besar pada paruh kedua 2008 antara lain adalah Cepu (dikelola oleh Mobil Cepu Ltd) dan Duri (dikelola oleh Chevron Texaco Indonesia d/h Caltex Pacific Indonesia). Lalu alasan kedua, pemerintah sedang mengkaji untuk menerapkan pola produksi minyak berkelanjutan, yakni produksi dipatok pada angka bph tertentu, sehingga cadangan minyak tidak akan cepat habis.
Pola produksi minyak berkelanjutan ini pada prinsipnya adalah menerapkan keseimbangan antara cadangan minyak dan produksinya. Namun, penulis mengingatkan bahwa secara tipikal sumur minyak di Indonesia berbeda dengan di Arab Saudi dimana sebuah sumur memiliki cadangan yang sangat besar. Sumur minyak di Indonesia, yang umumnya sumur-sumur kecil, tentu tidak akan efisien jika tidak `digenjot` produksinya sejak produkdi dimulai. Muncul pertanyaan kemudian, layakkah jika pola produksi minyak berkelanjutan ini diimplementasikan di Indonesia?
Ke-tidakkonsisten-an kebijakan pemerintah, kembali terjadi ketika baru dua pekan lalu, yakni pada 15 Februari 2008, pemerintah kembali mengumumkan, bahwa asumsi harga minyak `disesuaikan` lagi menjadi US$83 per barel, dan lifting minyak kembali direvisi menjadi hanya 910 ribu bph. Khalayak yang awam akan perhitungan pendapatan dan belanja negara saja bisa menyimpulkan bahwa kebijakan di sektor minyak dan bumi di negeri ini sangatlah rapuh (volatile), plin-plan dan cenderung bersifat trial and error.
Kebijakan revisi terakhir ini menjadi semakin lucu, dan tidak `nyambung` dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan satu bulan sebelumnya, yakni pada pertengahan Januari 2008. Ketika itu pemerintah memberikan insentif bagi pengusaha di sektor migas berupa penurunan pajak impor hingga nol persen, alias pembebasan pajak bagi barang-barang impor yang diperuntukkan bagi industri migas. Insentif fiskal ini, apa lah tujuannya, kalau bukan memacu Pertamina dan para KPS/KBH untuk `menggenjot` produksi, untuk mencapai target lifting minyak hingga 1 juta bph sebagaimana dipatok pemerintah semula?
Tapi biarlah, toh kebijakan pemerintah yang orang Jawa bilang `isuk dele, sore tempe` itu telah terjadi. Hari-hari ini, harga minyak telah mulai merangkak jauh di atas angka psikologis US$100 per barel. Analis bursa komoditas internasional bahkan memprediksi bahwa tingginya harga minyak ini bakal berlangsung lama. Berbicara dampak, jangankan bagi industri besar, lha wong industri tempe saja, yang notabene kedelainya sebagai bahan baku ternyata memiliki komponen impor, karena produksi kedelai dalam negeri tak mencukupi, pun terkena dampak. Dapat dibayangkan betapa parahnya negeri ini, mengingat komoditas remeh semacam tempe pun, tidak terlepas penghitungannya pada denominasi dolar. Lalu, muncul pertanyaan kemudian adalah, ke depan, apa yang harus dilakukan? Jawabnya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Namun izinkan penulis hanya mempersempit hanya dalam kebijakan di sektor hulu pengelolaan minyak dan gas bumi.
Beberapa hal yang layak dilakukan dalam kebijakan sektor hulu migas, adalah pertama, memacu produksi migas nasional. Sejumlah kendala (barrier) dalam hal produksi, sedapat mungkin dieliminasi. Pemerintah selayaknya memfasilitasi pengusaha migas yang saat ini mencoba memanfaatkan kesempatan, ‘aji mumpung’ dengan harga minyak tinggi, untuk menghidupkan kembali sumur-sumur minyak marginal (bercadangan dan berproduksi kecil) maupun sumur-sumur yang mulai kering (depleted well). Insentif fiskal berupa pembebasan pajak impor, bolehlah dilakukan. Dalam hal ini, masih ada waktu untuk kembali merevisi lifting dalam APBN 2008, pada angka di atas 1 juta bph. Sebab angka lifting 910 ribu bph, toh telah dapat dicapai pada 2007. Pemain migas sebagian besar sangatlah yakin bahwa lifting minyak kita masih mampu untuk digenjot di atas 1 juta bph. Dengan dipatoknya lifting minyak pada angka tinggi, maka pemain migas hulu akan termotivasi. Lalu, karena masih ada selisih antara produksi dan subsidi pemerintah yang wajib diberikan kepada rakyat, diharapkan windfall profit masih akan tetap diraih secara signifikan. Tentunya, pada saat yang sama, kampanye tentang penghematan energi masihlah harus terus dilakukan.
Kedua, percepat konversi energi dari minyak tanah ke gas bumi, dengan memperkuat sosialisasi pada tataran masyarakat akar rumput (grass root) yang umumnya dilingkupi tentang ketidakmengertian akan program konversi energi yang dilakukan pemerintah, karena kurangnya sosialisasi. Angka target konversi energi yang juga telah di-revisi dari 2 juta kilo liter, menjadi 1 juta kilo liter, dapat dikembalikan ke target semula, dengan syarat bahwa pemerintah dan Pertamina sudi bekerja keras melakukan sosialisasi.
Ketiga, walaupun ini berat untuk diimplementasikan, ajak perusahaan migas swasta untuk turut `berbagi.` Dalam hal ini, pemerintah berhak memungut pajak bagi KPS atau KBH atas windfall profit yang diterimanya.
Usulan kebijakan di atas, hanya dapat dilaksanakan, dengan niatan kuat pemerintah, dan mau bekerja keras, memiliki visi yang kuat untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat. Jika pemerintah terus mengikuti alur emosi yang selalu bimbang, tidak konsisten dalam kebijakan, maka tentu kita tidak akan dapat menikmati berkah dari melambungnya harga minyak dunia ini. Semoga.###
*) Edy Hafidl, adalah pendiri Forum Kajian Energi dan Mineral Indonesia (Forkei) Jakarta. Konsultan independen perusahaan migas asing. CEO MRChemindo Oil and Gas Services. Tulisan ini adalah pendapat pribadi.
Harga Minyak dan Kebijakan Sektor Hulu Migas
Edy Hafidl*
Harga minyak mentah dunia kembali mencatat rekor baru, yakni mencapai US$103,05 per barel pada perdagangan komoditas akhir pekan, sebuah pencapaian harga yang tak pernah terjadi dalam sejarah perdagangan minyak dunia. Dampak negatif lonjakan harga minyak—yang telah terjadi sejak paruh kedua 2007—telah banyak diulas, telah nampak di depan mata, bahkan telah dialami oleh sebagian besar anak negeri. Dahulu, jika harga minyak dunia naik, maka negara akan mendapatkan `rezeki nomplok`, yakni apa yang dinamakan dengan windfall profit. Namun, kini, alih-alih mendapatkan rezeki nomplok, lifting (asumsi tingkat produksi) minyak di APBN 2008 justru diturunkan, sementara ironisnya, pajak barang impor untuk kegiatan minyak dan gas bumi (migas) justru diturunkan hingga nol persen.
Apa yang salah dalam kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi di negeri ini? Harga minyak dunia naik, mengapa windfall profit tak bisa diraih oleh negara kita? Disadari atau tidak, secara ekonomi-politik, sebenarnya kebijakan tentang pengelolaan minyak dan gas bumi suatu negara, adalah cermin dari karakter kepemimpinan sebuah negara. Sejarah membuktikan bahwa karakter kepemimpinan kepala negara, akan memiliki implikasi langsung ataupun tidak langsung, terhadap implementasi kebijakan di sektor minyak dan gas bumi. Tengoklah kepemimpinan Fidel Castro yang non-kompromis—untuk tidak dikatakan otoriter— yang dengan tanpa kompromi menasionalisasi perusahaan-perusahaan migas asing. Namun, selayaknya, terlepas apapun karakter kepemimpinan negara, kebijakan tak lain haruslah ditujukan bagi kepentingan negara: untuk pencapaian kemakmuran rakyatnya.
Entahlah mazhab ekonomi energi mana yang dianut negeri ini. Sejumlah hal yang terjadi di negeri ini berkaitan dengan kebijakan di sektor minyak dan gas bumi sejak paruh kedua 2007 hingga hari ini, sangatlah menggelikan, plin-plan, tidak jelas. Biarlah masyarakat yang akan menilai, apakah ada kaitan antara kebijakan di sektor energi minyak dan gas bumi ini, dengan karakter pemimpin negeri ini.
Simaklah secara kronologis, apa yang terjadi sejak 16 Agustus 2007. Ketika itu, pada Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2008, presiden mengumumkan asumsi harga minyak di APBN 2008 sebesar US$60 per barel, dengan lifting minyak dalam RAPBN 2008 sebanyak 1,034 juta barel per hari (bph). Untuk diketahui khalayak bahwa urgensi peghitungan asumsi harga minyak dunia dan lifting minyak di APBN adalah untuk mengetahui seberapa besar pendapatan negara dari sektor minyak dan gas bumi. Jadi, rumus untuk asumsi pendapatan negara dari migas di APBN adalah: asumsi harga minyak dunia, dikalikan asumsi lifting minyak, dikalikan hari produksi di tahun takwim, maka didapatkankanlah pendapatan negara dari sektor migas.
Namun, melihat kecenderungan harga minyak dunia yang merangkak naik, ditambah lagi dengan pesimisme tentang kemampuan pemerintah/Pertamina dan kontraktor production sharing (KPS) migas atau kontraktor bagi hasil (KBH) dalam pencapaian peningkatan produksi, maka, tepat satu bulan setelah itu, yakni 17 September, setelah melakukan rapat kerja dengan DPR, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral merevisi lifting minyak 2008, menjadi hanya maksimal 1 juta bph.
Khalayak terpaksa harus menerima penjelasan tentang alasan `penyesuaian` lifting itu dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yakni pertama, produksi minyak terbesar baru bisa dicapai pada semester kedua 2008. Beberapa lapangan minyak yang akan memproduksi minyak skala besar pada paruh kedua 2008 antara lain adalah Cepu (dikelola oleh Mobil Cepu Ltd) dan Duri (dikelola oleh Chevron Texaco Indonesia d/h Caltex Pacific Indonesia). Lalu alasan kedua, pemerintah sedang mengkaji untuk menerapkan pola produksi minyak berkelanjutan, yakni produksi dipatok pada angka bph tertentu, sehingga cadangan minyak tidak akan cepat habis.
Pola produksi minyak berkelanjutan ini pada prinsipnya adalah menerapkan keseimbangan antara cadangan minyak dan produksinya. Namun, penulis mengingatkan bahwa secara tipikal sumur minyak di Indonesia berbeda dengan di Arab Saudi dimana sebuah sumur memiliki cadangan yang sangat besar. Sumur minyak di Indonesia, yang umumnya sumur-sumur kecil, tentu tidak akan efisien jika tidak `digenjot` produksinya sejak produkdi dimulai. Muncul pertanyaan kemudian, layakkah jika pola produksi minyak berkelanjutan ini diimplementasikan di Indonesia?
Ke-tidakkonsisten-an kebijakan pemerintah, kembali terjadi ketika baru dua pekan lalu, yakni pada 15 Februari 2008, pemerintah kembali mengumumkan, bahwa asumsi harga minyak `disesuaikan` lagi menjadi US$83 per barel, dan lifting minyak kembali direvisi menjadi hanya 910 ribu bph. Khalayak yang awam akan perhitungan pendapatan dan belanja negara saja bisa menyimpulkan bahwa kebijakan di sektor minyak dan bumi di negeri ini sangatlah rapuh (volatile), plin-plan dan cenderung bersifat trial and error.
Kebijakan revisi terakhir ini menjadi semakin lucu, dan tidak `nyambung` dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan satu bulan sebelumnya, yakni pada pertengahan Januari 2008. Ketika itu pemerintah memberikan insentif bagi pengusaha di sektor migas berupa penurunan pajak impor hingga nol persen, alias pembebasan pajak bagi barang-barang impor yang diperuntukkan bagi industri migas. Insentif fiskal ini, apa lah tujuannya, kalau bukan memacu Pertamina dan para KPS/KBH untuk `menggenjot` produksi, untuk mencapai target lifting minyak hingga 1 juta bph sebagaimana dipatok pemerintah semula?
Tapi biarlah, toh kebijakan pemerintah yang orang Jawa bilang `isuk dele, sore tempe` itu telah terjadi. Hari-hari ini, harga minyak telah mulai merangkak jauh di atas angka psikologis US$100 per barel. Analis bursa komoditas internasional bahkan memprediksi bahwa tingginya harga minyak ini bakal berlangsung lama. Berbicara dampak, jangankan bagi industri besar, lha wong industri tempe saja, yang notabene kedelainya sebagai bahan baku ternyata memiliki komponen impor, karena produksi kedelai dalam negeri tak mencukupi, pun terkena dampak. Dapat dibayangkan betapa parahnya negeri ini, mengingat komoditas remeh semacam tempe pun, tidak terlepas penghitungannya pada denominasi dolar. Lalu, muncul pertanyaan kemudian adalah, ke depan, apa yang harus dilakukan? Jawabnya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Namun izinkan penulis hanya mempersempit hanya dalam kebijakan di sektor hulu pengelolaan minyak dan gas bumi.
Beberapa hal yang layak dilakukan dalam kebijakan sektor hulu migas, adalah pertama, memacu produksi migas nasional. Sejumlah kendala (barrier) dalam hal produksi, sedapat mungkin dieliminasi. Pemerintah selayaknya memfasilitasi pengusaha migas yang saat ini mencoba memanfaatkan kesempatan, ‘aji mumpung’ dengan harga minyak tinggi, untuk menghidupkan kembali sumur-sumur minyak marginal (bercadangan dan berproduksi kecil) maupun sumur-sumur yang mulai kering (depleted well). Insentif fiskal berupa pembebasan pajak impor, bolehlah dilakukan. Dalam hal ini, masih ada waktu untuk kembali merevisi lifting dalam APBN 2008, pada angka di atas 1 juta bph. Sebab angka lifting 910 ribu bph, toh telah dapat dicapai pada 2007. Pemain migas sebagian besar sangatlah yakin bahwa lifting minyak kita masih mampu untuk digenjot di atas 1 juta bph. Dengan dipatoknya lifting minyak pada angka tinggi, maka pemain migas hulu akan termotivasi. Lalu, karena masih ada selisih antara produksi dan subsidi pemerintah yang wajib diberikan kepada rakyat, diharapkan windfall profit masih akan tetap diraih secara signifikan. Tentunya, pada saat yang sama, kampanye tentang penghematan energi masihlah harus terus dilakukan.
Kedua, percepat konversi energi dari minyak tanah ke gas bumi, dengan memperkuat sosialisasi pada tataran masyarakat akar rumput (grass root) yang umumnya dilingkupi tentang ketidakmengertian akan program konversi energi yang dilakukan pemerintah, karena kurangnya sosialisasi. Angka target konversi energi yang juga telah di-revisi dari 2 juta kilo liter, menjadi 1 juta kilo liter, dapat dikembalikan ke target semula, dengan syarat bahwa pemerintah dan Pertamina sudi bekerja keras melakukan sosialisasi.
Ketiga, walaupun ini berat untuk diimplementasikan, ajak perusahaan migas swasta untuk turut `berbagi.` Dalam hal ini, pemerintah berhak memungut pajak bagi KPS atau KBH atas windfall profit yang diterimanya.
Usulan kebijakan di atas, hanya dapat dilaksanakan, dengan niatan kuat pemerintah, dan mau bekerja keras, memiliki visi yang kuat untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat. Jika pemerintah terus mengikuti alur emosi yang selalu bimbang, tidak konsisten dalam kebijakan, maka tentu kita tidak akan dapat menikmati berkah dari melambungnya harga minyak dunia ini. Semoga.###
*) Edy Hafidl, adalah pendiri Forum Kajian Energi dan Mineral Indonesia (Forkei) Jakarta. Konsultan independen perusahaan migas asing. CEO MRChemindo Oil and Gas Services. Tulisan ini adalah pendapat pribadi.